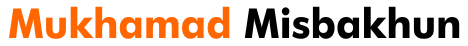Upaya menggenjot target penerimaan pajak sebesar Rp 1.484,6 triliun dalam RAPBN 2015 itu tidak hanya dengan menyadarkan masyarakat tentang pentingnya kewajiban pajak, tapi juga terciptanya efek jera bagi mereka yang secara sengaja mengabaikan kewajiban tersebut. Salah satu kebijakan strategis tersebut adalah penyanderaan (gijzeling) wajib pajak (WP) yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Upaya ini tentu saja tidak dilakukan dengan serta-merta. Gijzeling bahkan merupakan langkah terakhir setelah berbagai tahap penagihan dilakukan dengan optimal dan tidak juga membuahkan hasil. Ini tertuang dalam UU No 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
Pada Pasal 1 Angka 21 disebutkan penyanderaan sebagai pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu. Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap penanggung pajak yang mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) tanpa itikad baiknya untuk melunasi kewajibannya.
Kesadaran Masyarakat
Salah satu konsiderans yang menjadi referensi utama UU tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa adalah mendorong kesadaran, pemahaman, dan penghayatan masyarakat bahwa pajak adalah sumber utama pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Atas dasar kesadaran itulah penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu melibatkan peran aktif masyarakat dalam melaksanakan dan memenuhi sendiri kewajiban perpajakannya.
Formulasi kesadaran tersebut tidak terlepas dari pemahaman yuridis tentang perpajakan yang merupakan ranah hukum administrasi negara, dimana sanksi utamanya bukan pemenjaraan. Substansi administratif muncul sebagai akibat kelalaian
dalam melaksanakan kewajiban yang muncul dalam hubungan administrasi. Karena itulah pemberian sanksi didahului dengan pemberian peringatan lisan atau tertulis sampai dengan pengenaan sanksi administrasi yang bersifat dilaksanakan segera. Penyanderaan dalam hukum pajak itu sendiri tidak didasarkan pada putusan pengadilan, namun keputusan administrasi.
Penyanderaan sebagai sanksi dalam hukum pajak bukanlah kebijakan baru. Kebijakan ini awalnya telah diatur dalam UU No 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa. Namun, karena pertimbangan perikemanusiaan, tidak ada WP yang disandera oleh juru sita pajak berdasarkan aturan tersebut. Bahkan lembaga sandera dicabut oleh Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 2 Tahun 1964. Sejalan dengan itu Dirjen Pajak mengeluarkan Surat Edaran Nomor 06/Pj.4/1979 yang membekukan penyanderaan untuk penagihan pajak.
Namun, melalui SEMA Nomor MA/Pemb/0109 pada 11 Januari 1984 tentang Penegasan Pencairan Kembali Lembaga Sandera dalam Kaitannya dengan Efisiensi dan Kelancaran Penagihan Pajak untuk Kepentingan Negara, MA menyatakan penyanderaan yang dilarang adalah yang berkaitan dengan penerapan Pasal 209-233 HIR.
Penerapan kebijakan yang sama saat ini menjadi menarik perhatian disebabkan dukungan yang luas dari berbagai kalangan. Asosiasi pengusaha, asosiasi profesi, dan konsultan pajak maupun akademisi memberikan respons positif atas langkah DJP ini. Hal ini mengindikasikan sedikitnya tiga (3) hal. Pertama, meluasnya kesadaran akan pentingnya pajak sebagai sumber penerimaan negara.
Kedua, kepercayaan yang meningkat pada aparat pajak dalam melakukan penyanderaan sebagai sanksi administrasi yang keras dan merupakan upaya terakhir agar Wajib Pajak melakukan kewajibannya. Ketiga, kontribusi penerimaan pajak mendominasi penerimaan negara dalam struktur APBN. Penerimaan negara dengan sumber terbesar dari pajak memberikan konsekuensi tingginya tuntutan atas kinerja pemerintah untuk mensejahterakan rakyat.
Buah Reformasi
Kesadaran masyarakat juga tidak terlepas dari upaya reformasi sektor perpajakan yang tahap pertamanya berlangsung pada 2002 – 2009. Terdapat dua aspek yang menjadi prioritas perubahan, yaitu reformasi administrasi dan reformasi kebijakan. Reformasi administrasi meliputi restrukturisasi organisasi, perbaikan proses bisnis, dan penyempurnaan sistem manajemen sumber daya manusia. Reformasi kebijakan dilakukan dengan amendemen beberapa undang-undang di bidang perpajakan dan pemberian stimulus fiskal.
Tahap kedua reformasi perpajakan berlangsung dalam rentang waktu 2009 – 2012. Dalam tahap ini, perubahan difokuskan pada pengembangan sumber daya manusia dan penggunaan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan.
Mengingat tanggung jawab besar di pundak aparat pajak, reformasi perpajakan itu perlu dilanjutkan dengan arah yang semakin strategis. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya amanah yang harus dijalankan. Beberapa hal strategis yang perlu dilakukan dalam waktu dekat dapat dijabarkan dalam beberapa langkah.
Pertama, peningkatan kapasitas DJP. Permasalahan ini sudah menjadi langganan untuk disampaikan pada DPR, namun tak mudah untuk mencari jalan keluar. Persoalan ini tak lepas dari moratorium penerimaan pegawai baru, yang merupakan kewenangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara/Reformasi Birokrasi (PAN/ RB). Persoalan ini pula yang mendorong keinginan DJP untuk berdiri terpisah dari Kementerian Keuangan, dengan menjadi sebuah badan tersendiri. Dengan demikian DJP akan memiliki kebebasan dalam merekrut SDM, terutama dalam kaitannya untuk meningkatkan ekstensifikasi penerimaan pajak.
Kedua, peningkatan kesejahteraan pegawai DJP. Dalam catatan penulis, remunerasi pegawai DJP sejak tahun 2007 lalu tak pernah dinaikkan. Keberhasilan reformasi perpajakan, walaupun dengan sejumlah catatan, mesti dijaga momentumnya.
Motivasi pegawai harus dijaga agar tetap optimal dalam memberikan hasil terbaik bagi negara. Tanggung jawab besar untuk menjamin terpenuhinya penerimaan negara harus diiringi dengan dimilikinya kebanggaan dan jaminan bagi terpenuhinya kebutuhan pegawai secara layak.
Ketiga, diperlukan UU baru dalam ranah hukum pajak. UU baru tersebut harus memberikan jaminan yang lebih kuat bagi para penyidik pajak. Para penyidik pajak ini mesti mendapatkan perlindungtan hukum yang kuat agar dalam menjalankan kewenangannya agar mereka tidak mendapat persoalan hukum di kemudian hari.
Pada akhirnya, kita layak memberikan apresiasi atas berbagai kebijakan strategis dan terobosan siginifikan pemerintah dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak. Kita berharap target penerimaan pajak yang begitu besar bukan sekadar proyeksi ambisius melainkan aktualisasi dari konsistensi pemerintah dalam meniti jalan reformasi perpajakan itu sendiri yang pada gilirannya membuahkan kesadaran dan hasil yang bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia.
Dimuat di beritastu.com